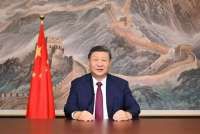Reporter: Amailia Putri Hasniawati |
JAKARTA. Sejak bea keluar (BK) biji kakao mulai diberlakukan April 2010 lalu, eksportir membebankan ongkos BK tersebut kepada petani sebesar Rp 3.000 per kilogram. Alasannya, eksportir enggan merugi. Terang saja petani kewalahan dengan ulah eksportir ini. Soalnya, dengan BK yang dibebankan pada mereka, pendapatan mereka berkurang.
Hassanuddin, petani kakao asal Sulawesi Tengah mengaku, bayaran untuk kakao yang dijualnya kini lebih rendah dari sebelum pemberlakuan BK. Jika sebelumnya harga kakao Rp 22.000-Rp 23.000 per kg di tingkat pedagang di kota, kini ia hanya menerima Rp 19.000-Rp 20.000 per kg.
“Kami berharap, eksportir menjadikan petani sebagai aset, karena kami yang menyediakan suplai, kita kan sama-sama membutuhkan,” keluhnya. Ia sangat menyayangkan sikap eksportir yang membebankan seluruh BK ke petani. Soalnya, petani hanyalah warga kecil yang menggantungkan hidupnya pada kakao.
Menurut Hasanuddin, bila pengurangannya hanya hanya Rp 1.000-Rp 1.500 per kg, ia tidak keberatan. Namun, karena potongannya mencapai RP 3.000 per kg, hitungan itu sangat memberatkannya. Itu sebabnya, petani minta agar eksportir tidak membebankan seluruh biaya BK kepada petani karena keduanya sama-sama saling membutuhkan.
Sekadar mengingatkan, pemberlakuan BK biji kakao yang tadinya 0% dikenakan secara progresif. Ketentuannya, jika harga rata-rata kakao di New York Board of Trade (NYBOT) di bawah US$ 2.000 per ton, maka tarif BK 0%.
Tapi jika harga rata-rata kakao US$ 2.000-US$ 2.750 per ton, maka BK-nya sebesar 5%. Lalu ketika harga kakao di atas US$ 2.750-3.500 per ton maka BK-nya sebesar 10%. Sedangkan saat harga melampaui US$ 3.500, maka BK yang dikenakan adalah 15%.
Dengan hitungan BK kakao itu, Hassanuddin minta agar beban BK dibagi dua, sama ratanya dengan eksportir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


/2010/06/03/1500831620.jpg)