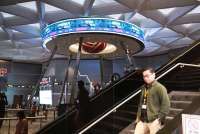Reporter: Rika Theo |
PANGKAL PINANG. Tiga bulan terakhir sungguh menjadi pukulan berat bagi semua orang yang bekerja di pertambangan timah. Harga timah di London Stock Exchange yang selama ini menjadi acuan harga timah mencapai US$ 19.300 per metriks ton pada Jumat (23/12). Masa indah, harga timah mencapai puncaknya sebesar US$ 33.300 pada April lalu berlalu sudah.
Jaka (39) tampak bersantai di tempat tinggalnya, sebuah gubuk bertenda biru yang berdiri di tengah areal pertambangan Air Jangkang, Merawang, Bangka. Sehari-harinya Jaka adalah penambang timah upahan di tambang inkonvensional (TI) yang menjadi mitra PT Timah Tbk. Hari itu, ia libur menambang karena hujan turun. Selain lebih sulit dan lebih boros biaya, menambang ketika hujan sama saja mencari risiko. Medan penambangan akan berbahaya, belum lagi petir yang mudah menyambar di tanah berkadar logam tinggi itu.
Jaka harus merelakan rezekinya berkurang. Tak hanya karena cuaca, ia cuma bisa pasrah ketika upahnya harus dipangkas separuh. “Harga timah turun, jadi upah berkurang. Sekarang susah, Mbak, tenaga kerja di sini pada mengeluh, bos-bos juga banyak yang ngangkatin alat-alat,” tutur pekerja pendatang dari Lampung ini.
Harga timah dunia menyusutkan harga jual timah di kalangan petambang. Dari kisaran Rp 100.000-an per kg di Juli lalu, harga jual pasir timah basah di tambang itu kini hanya Rp 45.000-Rp 50.000 per kg. Alhasil, sebagian TI memilih mengurangi operasionalnya ketimbang merugi.
Sekarang, Jaka dan dua orang rekannya menerima upah Rp 7.000 untuk setiap kg pasir timah yang mereka dapatkan. Padahal pertengahan tahun lalu, upahnya mencapai Rp 16.000 per kg. Pendapatan Jaka merosot drastis. Ketika harga timah tinggi, ia bisa meraup Rp 5 juta-Rp 7 juta per minggu. Sekarang, ia harus puas mengantongi Rp 1 juta per minggu dengan bekerja sekitar 10 jam per hari.
Jaka adalah salah satu dari sekian banyak pekerja pendatang dari luar Bangka yang terpikat timah. Mereka dikenal dengan istilah fenomena tenda biru. Sebab, para pekerja ini tinggal di tenda-tenda biru di kawasan pertambangan.
Cerita yang mirip datang dari Andi Abdurrohim, pemilik TI apung atau penambang timah lepas pantai di Desa Batu Belubang, Pangkalpinang, Bangka. Seperti kebanyakan penduduk desa ini, Andi tadinya seorang nelayan.
Namun, tiga tahun lalu ia mulai banting setir menjadi penambang. Ia mulai dengan menjadi penyelam yang mencari timah di pinggir pantai dengan peralatan terbatas. Dengan bantuan modal yang didapat seorang cukong kolektor, ia membeli sebuah ponton atau perahu penambang yang harganya sekitar Rp 60 juta-Rp 70 juta.
Berbekal alat ini, rezekinya mengalir lancar hingga ia berhasil melunasi pinjaman dan lepas dari jeratan utang si cukong. Bahkan, ia bisa membeli dua kapal ponton lagi serta memiliki 9 pekerja. Dengan skema bagi hasil, ia juga meminjam satu ponton miliknya ke tetangga.
Namun, kini Andi mengaku kesulitan. “Minggu lalu saya dapat 102 kg, setelah dipotong pengeluaran, yang tersisa di tangan tinggal Rp 250.000,” ujarnya. Dengan harga jual pasir timah hanya Rp 50.000, Andi hanya memperoleh Rp 5 juta.
Pendapatan ini harus dipotong upah pekerja sekitar Rp 2,5 juta, minyak solar Rp 2,22 juta, dan biaya lain-lain seperti makan pekerja. Kondisi ini jauh berbeda dengan beberapa bulan lalu ketika ia bisa menjual pasir timah dalam jumlah yang sama seharga Rp 10 juta.
Meski harga anjlok, Andi terus menambang setiap hari. Ia berharap bisa menemukan pasir timah dalam jumlah besar untuk menutup murahnya harga. Saban hari, minimal, ia harus mendapatkan 20 kg timah. “Rezeki itu sewaktu-waktu dikasih sama Yang Kuasa. Kalau tidak menambang, penghasilan datang dari mana,” ujar pria Bugis yang hijrah ke Bangka tahun 1990-an itu.
Untuk menambal pendapatan, Andi juga mulai mencari ikan lagi. Ia juga mengandalkan usaha kios pulsa di depan rumahnya. Sayangnya, penjualan pulsa pun ikut turun. “Sepi, biasanya sehari bisa 150 pembeli, sekarang cuma 30-50 pembeli,” keluhnya.
Timah memang menggerakkan ekonomi desa di tepi pantai itu. Dari 3.000 penduduk, kata Andi yang juga menjabat ketua RT setempat, 1.700 merupakan warga pendatang. Mereka nekat menjadi TI apung ilegal. Maklum, penghasilan yang didapat lebih besar ketimbang jadi nelayan. Masalahnya, ketika harga timah jatuh, harapan itu pupus. “Sekarang sudah sekitar 300 orang meninggalkan kampung,” ungkap Andi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


/2011/12/28/594302878.jpg)